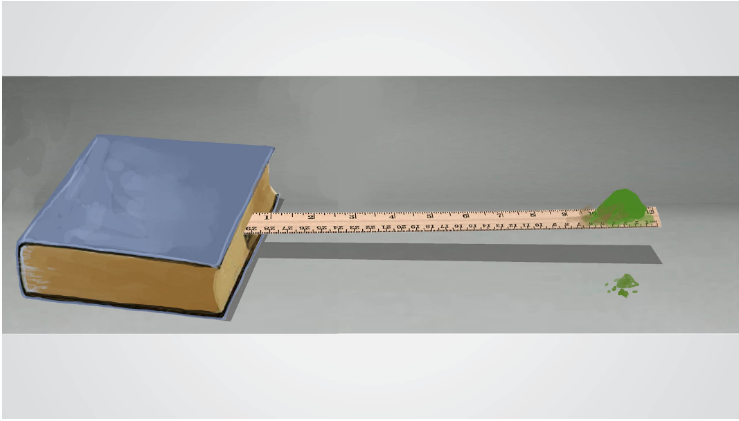
JAWA Tengah, 1993, pemerintah sedang membangun waduk Kedungombo. Masyarakat mencoba mempertahankan tanah mereka meski mendapat banyak tekanan agar menyingkir dari area waduk untuk pembangkit listrik tenaga air itu. Seberkas putusan datang dari Jakarta. Majelis hakim kasasi Mahkamah Agung yang dipimpin Zaenal Asikin Kusumaatmadja mengabulkan permohonan ganti rugi masyarakat di tiga kabupaten dengan jumlah yang lebih tinggi dibanding yang mereka minta. Putusan Zaenal juga menyatakan menolak prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tidak adil. Sayangnya, pada November 1994, putusan itu dikoreksi majelis hakim Mahkamah Agung yang dipimpin Purwoto Gandasubrata dalam mekanisme peninjauan kembali.
Jawa Tengah, 2022, pemerintah sedang membangun bendungan Bener. Batu untuk fondasinya akan diambil dari Desa Wadas, sekitar 10 kilometer dari lokasi pembangunan bendungan di Purworejo itu. Sebagian penduduk Wadas menolak dengan dalih penambangan akan melenyapkan sumber daya alam dan ruang hidup mereka, meski mendapat intimidasi dan kekerasan aparat negara. Tapi, tak seperti Kedungombo, tak ada kabar gembira dari Jakarta yang datang ke Wadas. Wacana pembebasan tanah untuk kepentingan umum, yang direvisi pada 1995 sebagai kelanjutan kasus Kedungombo, justru menjadi pembenaran pemerintah untuk mengusir warga Wadas. Bahkan bungkusnya lebih canggih: demi proyek strategis nasional dalam peraturan presiden.
Kisah dua bendungan di Jawa Tengah itu sangat mirip. Bukan hanya tentang hak-hak masyarakat yang dilanggar pemerintah, tapi juga peran hukum yang begitu kuat menjadi penopang dan dalihnya. Memang, fenomena penggunaan hukum untuk pembangunan bukan hal baru. Bahkan “hukum dan pembangunan” adalah sebuah gerakan yang sudah lama disorot, dikaji, dan dikritik. Akademikus hukum menyebutnya “gerakan” karena terjadi secara global dengan upaya sistematis memakai hukum untuk melancarkan pembangunan.
Di Indonesia, gerakan “hukum untuk pembangunan” begitu masif pada masa pemerintahan Soeharto (1965-1998). Akibatnya, perkembangan hukum Indonesia saat itu berlangsung cepat. Hukum dan pembangunan diletakkan dalam konteks neoliberalisme untuk menopang transaksi dagang antarnegara. Akibatnya marak apa yang disebut transplantasi hukum melalui proyek-proyek kerja sama pembangunan serta komitmen pada lembaga keuangan internasional. Hukum menjadi lebih teknokratis dan lembaga-lembaga dijauhkan dari proses politik yang terlalu rumit.
Rupanya, hukum dan pembangunan tidak berhenti pada transaksi perdagangan internasional. Gerakan ini juga telah menjadi cara pandang yang dominan tentang hukum itu sendiri. Hukum dilihat terutama sebagai instrumen pengatur ketertiban.
Cara pandang ini datang dari Roscoe Pound (1870-1964) lewat gagasan law as a tool of social engineering. Di Indonesia, ide ini diadopsi oleh Mochtar Kusumaatmadja, Menteri Kehakiman 1974-1978, pada 1980-an. Pandangan hukum sebagai alat rekayasa sosial bahkan dikenal sebagai sebuah teori hukum tersendiri yang melihat hukum sebagai instrumen pembaruan masyarakat Indonesia.
Saat mengembangkan gagasannya, Mochtar tentu tak membayangkan hukum yang melanggar hak asasi manusia dan merusak lingkungan. Namun cara pandang tentang fungsi hukum ini membuat nyaman penguasa Orde Baru. Hukum untuk pembangunan pun memerlukan stabilitas politik dan ketertiban yang berakibat peminggiran hak asasi dan kelestarian lingkungan.
Kata “pembangunan” di sini memang hanya berkhidmat pada angka-angka pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Soal tak menjangkau keadilan ekonomi dan kualitas manusia serta lingkungan hidup tak masuk definisi dan ruang lingkupnya. Padahal pembangunan dengan statistik dan infrastruktur akan selalu menyembunyikan fakta-fakta penting di baliknya tentang siapa yang menikmatinya? Berapa banyak warga yang terambil haknya? Seberapa rusak lingkungan sebagai akibatnya?
Penguasa menyukai hukum untuk pembangunan karena ia memiliki sifat memaksa (coercive) berupa keharusan, larangan, dispensasi, dan izin yang dikuatkan dengan sanksi dan hukuman. Kekuatan hukum memang efektif membuat sebidang tanah cepat berpindah tangan tanpa memerlukan pembahasan dan banyak pertemuan. Tanpa studi macam-macam, sebuah hutan lindung bisa berganti secara sah dan cepat menjadi perkebunan kelapa sawit dengan dalih menaikkan pajak untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Kita harus ingat bahwa hukum negara yang berbentuk peraturan perundang-undangan dibuat oleh aktor formal pembuat peraturan, yaitu pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, mereka dikontrol oleh kepentingan ekonomi, baik yang berada di dalam pemerintahan maupun yang secara tidak langsung mengontrol politik formal di luar gelanggang kekuasaan seperti dalang memainkan wayang.
Kelompok belakang layar yang kita sebut oligark itu bisa muncul dan membesar karena aturan main politik yang memungkinkan segelintir orang kaya memodali jalannya politik dalam pemilihan umum. Ambang batas pencalonan presiden, aturan dana kampanye dan dana partai politik yang longgar, juga partai politik yang tidak demokratis adalah pintu longgar para oligark dalam memainkan sistem demokrasi kita untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya melalui hukum yang sah. Di DPR, kontrol oligarki kian kuat karena pengambilan keputusan hukum dibuat di ruang-ruang tertutup dengan meminimalkan partisipasi publik.
Karena targetnya semata menumbuhkan ekonomi, perlindungan terhadap hak asasi dan lingkungan akan dianggap sebagai penghambat. Untuk mengenyahkannya, para aktor politik membuat atau memakai hukum, seperti dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri atau keputusan gubernur. Undang-Undang Cipta Kerja mengistimewakan ratusan proyek strategis nasional. Agar negara gampang merampas tanah masyarakat, ada serangkaian aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Begitu pula penegakan hukum. Aparat kepolisian kita menjadi garda depan penegakan aturan untuk pembangunan. Polisi kita tak segan melakukan kekerasan kepada para penolak proyek pembangunan kendati protes itu dilakukan demi hak hidup yang dijamin konstitusi dan hukum paling tinggi di Indonesia, yakni dasar negara: Undang-Undang Dasar 1945.
Sejak 2011, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi konsep free and prior informed consent atau FPIC. Gagasan ini muncul dalam proyek pengurangan emisi melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Konsep ini kemudian melebar ke semua masyarakat adat dan masyarakat lokal. Prinsipnya, FPIC memberi pengakuan kepada hak masyarakat untuk menyatakan “ya”, “bagaimana”, atau “tidak” terhadap sebuah proyek pembangunan yang mempengaruhi sumber daya dan wilayah mereka.
Banyak yang mengira era hukum sebagai panglima demi pembangunan sudah selesai begitu Soeharto jatuh. Namun kasus Wadas mengingatkan memori kita pada waduk Kedungombo yang menjadi monumen pelanggaran hak asasi manusia. Bedanya, hukum kini terasa lebih menindas karena tidak ada lagi hakim Zaenal Asikin yang berpihak kepada masyarakat. Para aktivis yang membela hak penduduk Wadas tak hanya mendapat kekerasan fisik dari aparat negara, mereka juga tak terlindungi dari serangan di dunia maya.
Bila pendekatan pembangunan Indonesia tak diubah, kasus-kasus pembangunan yang difasilitasi hukum tak akan berhenti di Wadas. Penembakan penolak tambang emas di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, atau penolakan pertambangan emas di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, adalah contoh bagaimana di banyak tempat pembangunan yang memakai hukum hanya menimbulkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Pertanyaannya: pembangunan ini untuk siapa dan dengan cara apa ia bisa selaras dengan hak asasi manusia?
Di zaman modern, pembangunan seharusnya bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang banyak. Di era Internet yang serba terbuka, pembangunan seharusnya tak hanya menguntungkan segelintir orang kaya seraya mengorbankan lebih banyak orang. Sejarah Orde Baru sudah membuktikan kekuasaan yang berpihak pada kroni tak menghasilkan pembangunan yang bermakna.
Pembangunan yang bermakna menuntut cara-cara manusiawi. Karena itu, dialog, partisipasi, dan keterbukaan harus menggantikan perintah, kekerasan, dan intimidasi dalam proyek-proyek pembangunan. Dengan pendekatan pembangunan semacam ini, hukum akan kembali menjadi instrumen untuk memfasilitasi penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia serta melindungi lingkungan yang menjadi ruang hidup kita bersama.
Penulis: Bivitri Susanti
Sumber: https://majalah.tempo.co/read/kolom/165374/memori-kedungombo-di-proyek-bendungan-bener
Dipublikasikan oleh:


