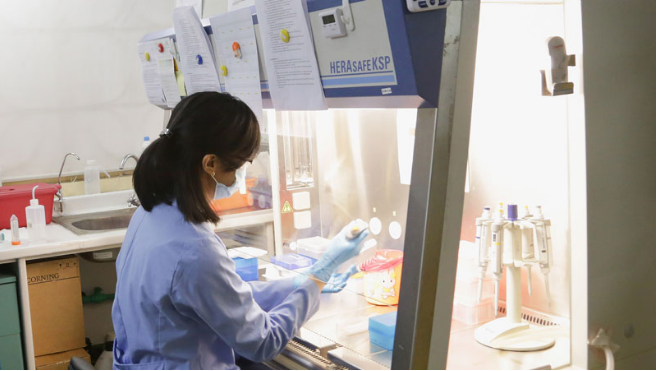
RISET yang dikungkung prosedur administrasi dan dibuat hanya untuk menghabiskan anggaran sebenarnya bukan cerita baru di negara ini. Namun lahirnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membawa dimensi baru yang membuatnya lebih rumit: politisasi lembaga penelitian melalui ideologisasi riset dan integrasi di bawah eksekutif.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) terbit karena keinginan pemerintah merapikan keruwetan dalam ekosistem penelitian di Indonesia. Aturan main baru ini berniat menata ulang pelbagai hal tentang penelitian agar ekosistem inovasi terdorong dan riset bermanfaat bagi kualitas hidup manusia.
Banyaknya ilmuwan dan peneliti yang enggan kembali ke Tanah Air setelah menempuh pendidikan di luar negeri, juga minimnya inovasi padahal sumber daya manusia Indonesia luar biasa banyak, sudah lama menggelisahkan banyak kalangan. Maka mengutamakan riset, memperbaiki tata kelola pengetahuan, dan meluaskan kemitraan lembaga riset dengan swasta digadang-gadang sebagai jawaban. Untuk menopang semua itu, lembaga riset harus dirapikan dulu dengan harapan tata kelola penelitian bisa lebih modern.
Semua cita-cita indah itu seperti dibajak di tengah jalan ketika Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan tentang BRIN pada 24 Agustus 2021. Kelahiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, yang menjadi turunan Undang-Undang Sisnas Iptek, juga diwarnai kejadian tak biasa dalam pembentukannya karena selama 17 bulan pemerintah membiarkan BRIN sebagai amanat undang-undang tak ternaungi aturan.
Awalnya, pemerintah membuat pengaturan transisi melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019. Pasal 36 menyebutkan peraturan ini berlaku sampai 31 Desember 2019. Sebelum habis masa berlakunya, Presiden menerbitkan Peraturan Nomor 95 Tahun 2019 yang memperpanjang pemberlakuannya hingga 31 Maret 2020. Meski masa transisi sudah diperpanjang, aturan tentang BRIN baru terbit pada Agustus 2021. Kabarnya, keterlambatan ini terjadi karena sejumlah orang berusaha menghadang peraturan presiden itu untuk mengubah desain BRIN.
Karena itu, isi peraturan presiden yang terlambat ini mengejutkan. Pasal 7 menyebutkan Ketua Dewan Pengarah BRIN secara ex officio berasal dari unsur dewan pengarah lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila. Tentu saja aturan itu mengarah ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang saat ini dipimpin Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai dengan suara terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat dan anggotanya menjadi presiden. Tugas dewan pengarah besar: berwenang memberikan arahan, masukan, evaluasi, persetujuan, atau rekomendasi kebijakan kepada BRIN.
Dengan kewenangan seperti itu, secara praktis akan ada koridor ideologi yang akan “dijaga” saat BRIN mengadakan berbagai riset dan inovasi. Padahal mengerangkeng lembaga ilmu pengetahuan sebagai unit ideologisasi justru menarik mundur ilmu pengetahuan. Para peneliti BRIN akan mendapat arahan—atau berkhidmat pada—bentuk pengetahuan tertentu yang dianggap sesuai dengan ideologi. Masalahnya bukan Pancasila sebagai ideologi Indonesia, melainkan ihwal membuat kurungan bagi sesuatu yang semestinya dikembangkan dan dibebaskan.
Tanpa penegasan bahwa peneliti harus berkhidmat pada ideologi saja, atas nama pengawasan, belakangan ini cukup banyak pembatasan bagi peneliti luar negeri untuk mengamati Indonesia dari dekat. Kita tahu pembatasan itu tak semata ditetapkan karena tujuan saintifik, tapi juga acap menjadi dalih menghalangi keterbukaan informasi karena penelitian tak sesuai dengan tujuan dan keinginan penguasa. Contohnya, pada Januari 2020, seorang peneliti hutan dideportasi karena menerbitkan hasil riset mengenai luas area kebakaran hutan 2019 yang lebih tinggi dibanding angka resmi pemerintah.
Politisasi berikutnya dalam pendirian BRIN adalah integrasi semua penelitian di bawah eksekutif. BRIN akan menjadi rumah baru bagi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, serta Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.
Integrasi ini tentu saja berimbas pada anggaran. BRIN akan menampung kegiatan berikut anggaran riset dan inovasi di semua kementerian dan lembaga negara. Dalam surat kepada presiden pada 23 September 2021, Kepala BRIN menguraikan sebaran anggaran riset dan inovasi di 64 kementerian dan lembaga, lalu meminta presiden menyetujui pengalihan anggarannya kepada lembaga yang dipimpinnya.
Pengalihan anggaran ini bisa jadi merupakan konsekuensi integrasi semua kegiatan riset dan inovasi ke dalam BRIN. Namun yang lebih penting dari integrasi adalah ada pengalihan semua peneliti ke lembaga ini, termasuk yang berada di lembaga-lembaga independen, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan cabang-cabang kekuasaan negara lain.
BRIN adalah lembaga dalam kuasa pemerintah. Adapun jabatan fungsional peneliti juga ada pada lembaga legislatif dan yudikatif, yang semestinya tidak berada di bawah kendali eksekutif. Di Dewan Perwakilan Rakyat ada Badan Keahlian yang menjadi rumah bagi puluhan peneliti. Mereka bertugas membantu anggota Dewan menjalankan fungsi legislasi ataupun pengawasan terhadap eksekutif. Begitu pula di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Ada banyak peneliti yang tak hanya melakukan riset. Mereka juga membantu hakim membuat putusan.
Bagaimana jadinya jika peneliti legislatif dan yudikatif berada dalam kendali eksekutif? Apa yang akan terjadi bila orang-orang yang bertugas membantu hakim membuat putusan dikontrol oleh eksekutif dan harus berada dalam koridor Pancasila, yang pemaknaannya dimonopoli oleh BPIP? Apa pula yang akan terjadi bila sumber daya manusia yang bertugas meriset penerapan undang-undang berada di bawah kendali eksekutif? Bisa dibayangkan, karakter putusan pengadilan dan produk-produk DPR akan sangat lekat dengan kepentingan pemerintah.
Model pengintegrasian seperti ini juga akan berpengaruh pada lembaga independen seperti Komnas HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar keberadaan Komnas HAM menyebutkan salah satu fungsi lembaga ini adalah melakukan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi perlindungan dan penegakan HAM. Sasaran Komnas HAM adalah pemerintah. Begitu pula Ombudsman, yang bertugas memberikan rekomendasi pelayanan publik oleh pemerintah. Integrasi membuat independensi dua lembaga ini menjadi hilang.
Model integrasi lembaga riset di bawah BRIN semacam ini agaknya akibat pemaknaan keliru pemerintah pada kata “terintegrasi” dalam Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Sisnas Iptek. Pasal ini menyebutkan BRIN bertugas mengintegrasikan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi. Bagian penjelasan pasal ini menyebutkan definisi “terintegrasi” adalah upaya mengarahkan dan menyinergikan berbagai aktivitas untuk menghasilkan invensi dan inovasi. Dari sini terlihat kata “terintegrasi” memunculkan dua alternatif interpretasi terkait dengan aspek kelembagaan, yaitu peleburan atau pengkoordinasian.
Pemerintah memilih makna integrasi sebagai peleburan secara maksimal. Dampaknya bisa positif karena akan terjadi efisiensi anggaran dan kemudahan dalam perencanaan serta pengawasan riset. Namun BRIN bukan unit administrasi biasa, melainkan pengelolaan pengetahuan. Riset dan inovasi tidak bisa berkembang di atas prinsip efisiensi dan kontrol yang berlebihan. Apalagi ada peran cabang-cabang kekuasaan lain yang seharusnya mengontrol pemerintah.
Bila politisasi riset melalui desain BRIN ini tak dihentikan, bukan hanya ekosistem riset Indonesia yang akan makin terpuruk demokrasi konstitusional pun bakal tergerus karena perangkat substansi lembaga-lembaga yang seharusnya mengawasi penguasa kini berada dalam kendali pemerintah.
Penulis: Bivitri Susanti
Sumber: https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/165076/bahaya-integrasi-brin-bagi-demokrasi-indonesia
Dipublikasikan oleh:


