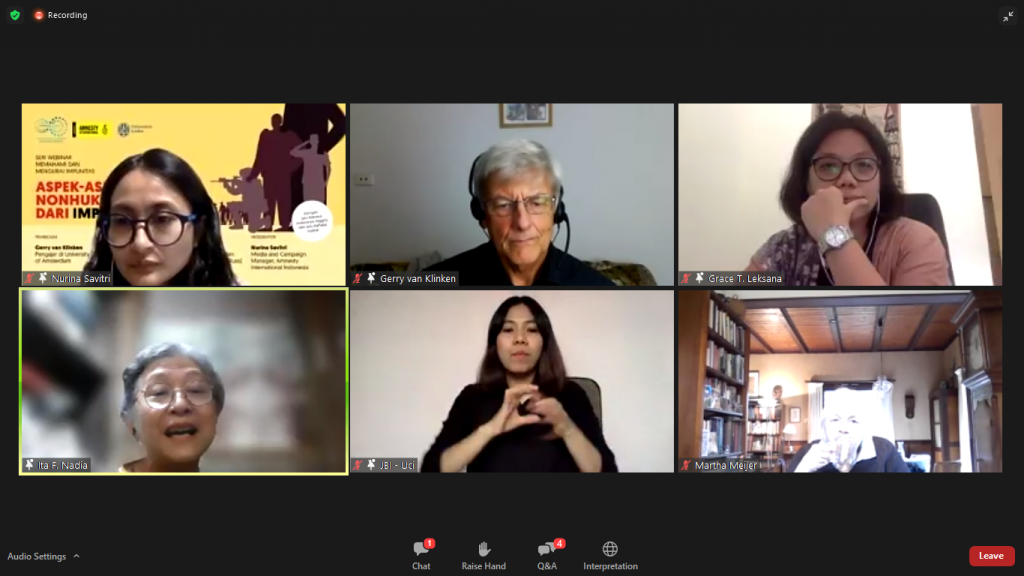
Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Amnesty International Indonesia, Kelompok Kerja Indonesia-Belanda untuk Keadilan dan Pembangunan, dan Institut Van Vollenhoven dari Leiden Law School menyelenggarakan diskusi bertajuk Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas pada Rabu (30/4/2022) secara daring. Diskusi ini adalah edisi ketiga dari rangkaian Seri Webinar: Memahami dan Mengurai Impunitas di Indonesia.
Dalam diskusi tersebut, pengajar jurusan sejarah Universitas Negeri Malang, Grace T. Laksana, memaparkan berbagai dinamika politik lokal yang memiliki pengaruh dalam peristiwa kekerasan 1965. Dalam studi kasus kekerasan 1965, terdapat hubungan sebab akibat yang sangat kompleks seperti adanya konstelasi politik seperti perubahan rezim dan aktor kekerasan yang terlibat sangat berlapis mulai dari militer hingga kelompok-kelompok sipil. Menurutnya, tidak mungkin kekerasan masif yang berskala nasional dapat terjadi tanpa campur tangan militer, tapi di sisi lain kekerasan tersebut juga dapat terjadi karena bantuan sipil (subcontracting violence).
“Menganalisa kekerasan dari sisi negara atau sisi militer saja tidak cukup, karena kita juga harus melihat politik atau dinamika lokal yang memungkinkan kolaborasi tersebut terjadi,” ungkapnya.
Salah satu contoh yang diangkat adalah dinamika politik lokal di Aceh. Mengutip studi Jess Melvin berjudul Berkas Genosida Indonesia: Mekanika Pembunuhan Massal 1965–1966, menunjukkan bahwa kekerasan bersifat struktural karena terdapat koordinasi antara militer nasional dan Aceh. Selain itu, terdapat pula dinamika lokal yang berkontribusi terhadap meluasnya kekerasan seperti adanya ketegangan antara pemerintahan daerah Aceh dan Sukarno.
Berdasarkan hal tersebut, menurut Grace, politik lokal bukanlah perpanjangan tangan atau replika dari politik nasional. Peristiwa 1965 juga memperlihatkan bahwa tidak hanya elit yang memanfaatkan sipil, tapi sipil juga memanfaatkan dan membangun jaringan dengan elit. Oleh karena itu, persoalan impunitas ini tidak hanya dilanggengkan oleh negara, tapi juga kelompok sipil di tingkat lokal yang mempertahankan status quo.
Sementara itu, pengajar University of Amsterdam, Gerry van Klinken membahas studi berjudul Nine-Tenths of the Law: Enduring Dispossession in Indonesia yang ditulis oleh Christian Lund. Studi tersebut mengangkat beberapa studi kasus, salah satunya adalah sejarah panjang konflik tanah perkebunan yang terjadi antara petani dan perusahaan agraria Lonsum. Perselisihan terus menerus yang terjadi antara perusahaan, petani, dan penguasa menimbulkan beberapa faktor-faktor yang tidak pernah hilang, seperti kedudukan lokal, kekerasan, serta upaya untuk “melegalisir” status dengan memperalat dokumen hukum tertentu dalam memperkuat posisi masing-masing pihak. Berdasarkan peristiwa tersebut, legalisasi bukanlah peradilan melainkan, “sandiwara yang serius” dengan sejarah panjang yang tidak mudah.
Ketua Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan (RUAS), Ita F. Nadia menuturkan bahwa keadilan bagi korban pelanggaran HAM terletak pada bagaimana mencari penjelasan atas apa yang terjadi dan dirasakan tanpa ada tekanan. Sejarah digunakan sebagai penjelasan tentang peristiwa masa lalu untuk membangun keadilan di masa depan. Hal-hal itulah yang mendasari terbentuknya Museum Bergerak, sebuah ruang sejarah untuk melakukan pengarsipan secara kolektif dan komunal yang tidak bergantung pada bangunan fisik.
“Museum Bergerak adalah salah satu bentuk baru dari rekonstruksi sejarah yang berasal dari pengalaman korban pelanggaran HAM, juga sebagai media untuk pendidikan sejarah dan kampanye melawan impunitas,” ungkapnya.
Diskusi yang dimoderatori oleh Media and Campaign Manager, Amnesty International Indonesia, Nurina Savitri bertujuan untuk mendukung upaya berbagai pihak dalam mengatasi masalah impunitas di Indonesia. Diskusi ini dapat disaksikan ulang di kanal YouTube STH Indonesia Jentera.
Unduh File:
STH Indonesia Jentera_Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas_Grace Leksana
STH Indonesia Jentera_Aspek-aspek Nonhukum dari Impunitas_Ita Fatia Nadia

