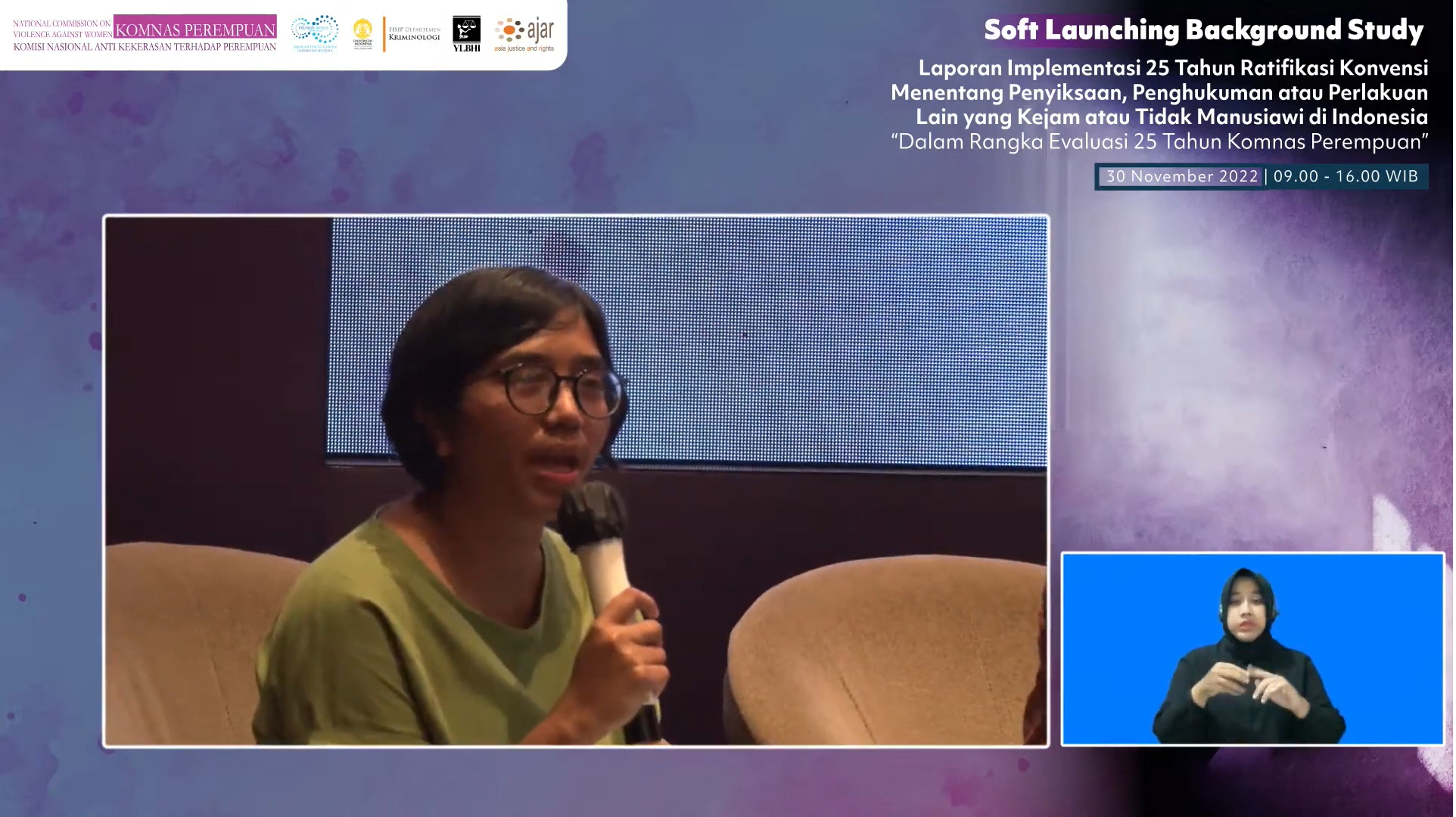
Kelompok minoritas dan pengungsi menjadi contoh kelompok rentan yang rawan menjadi korban perlakuan yang tidak manusiawi di Indonesia. Kelompok minoritas keagamaan misalnya, berulang kali mendapatkan ancaman kriminalisasi dan persekusi, baik yang dilakukan oleh lembaga negara atau organisasi kemasyarakatan. Hal tersebut terjadi karena masih ada beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan ruang yang adil bagi kelompok-kelompok yang memiliki keyakinan berbeda.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua STH Indonesia Jentera Bidang Pengabdian Masyarakat, Asfinawati, dalam Soft Launching Background Study: Laporan Implementasi 25 Tahun Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau Tidak Manusiawi di Indonesia pada 30 November 2022 di Jakarta. Laporan tersebut disusun oleh Komnas Perempuan bersama Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Asia Justice and Rights (AJAR), Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Lebih lanjut, Asfinawati menjelaskan bentuk-bentuk ancaman kriminalisasi yang kerap diterima oleh kelompok minoritas keagamaan adalah berupa amuk masa, pemaksaan untuk meninggalkan dan tidak diperbolehkan kembali ke kampung halaman, ditempatkan di lokasi pengungsian, dan pembatasan ruang gerak. Lokalisasi tersebut kemudian secara langsung berdampak pada terbatasnya akses kelompok minoritas keagamaan untuk mengakses kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. “Pola perlakuan pada kelompok minoritas ini terjadi diawali oleh stigmatisasi oleh masyarakat dan relasinya menjadi semakin buruk karena negara melakukan legalisasi terhadap stigma tersebut melalui aturan atau kebijakan,” ungkap Asfinawati.
Selain masyarakat yang terkoordinasi dalam beberapa kelompok, pemerintah dan aparat penegak hukum juga punya andil dalam pola perlakuan terhadap kelompok minoritas tersebut. Keterlibatan tersebut dimulai dari pola organisasi kemasyarakatan yang hadir untuk melakukan persekusi yang di banyak kasus berujung pada ancaman secara fisik. Asfinawati menjelaskan, selain karena faktor ideologi yang dominan, dasar dari perlakuan tersebut juga mendapat legitimasi dari negara melalui aturan UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama, yang memberikan dasar untuk membuat kelompok minoritas keagamaan atau keyakinan dianggap menodai agama. Pemerintah yang seharusnya menjadi mediator dengan pengambilan kebijakan yang berbasis bukti dan empati justru tidak menjalankan fungsinya secara maksimal.
Terkait peran negara, Asfin menegaskan terdapat permasalahan akuntabilitas yang patut menjadi perhatian. Pemerintah tidak dapat menjelaskan secara formil maupun materiil terkait implementasi kebijakan pemaksaan agar kelompok minoritas tersebut harus keluar dari lingkungan tempat tinggalnya. Hal tersebut juga diperparah dengan tidak adanya penanganan yang maksimal pada kelompok minoritas ketika tinggal di tempat pengungsian terkait hak dasar dan kehidupan yang layak. Dalam proses resolusi permasalahan, pemerintah juga tidak memberikan komitmen penanganan yang maksimal sehingga konflik berlarut dan tidak memberi kepastian kapan kelompok ini akan bisa kembali serta menjalani hidup yang baik di tempat tinggalnya.
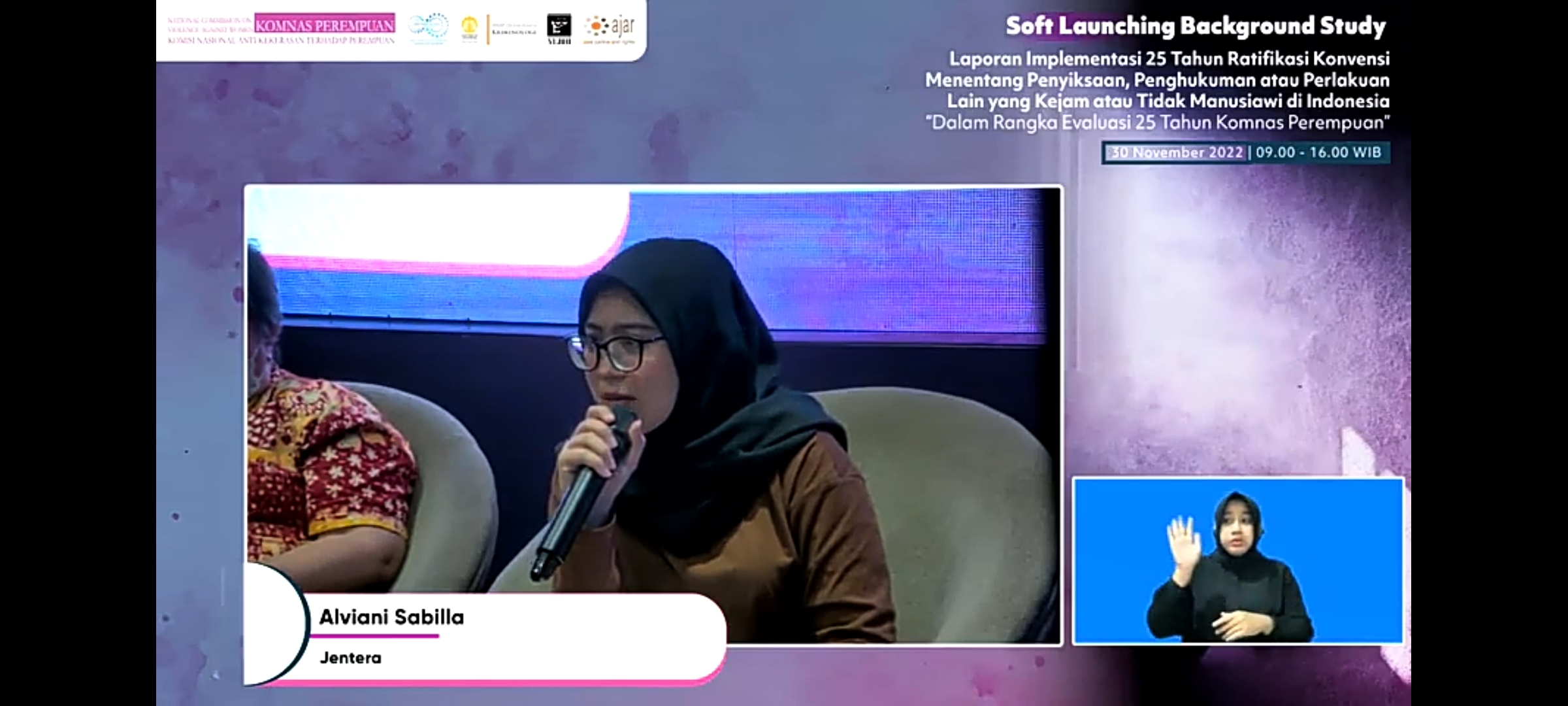
Asisten pengajar Jentera yang juga merupakan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Alviani Sabillah dan Johanna Poerba memperkaya laporan dengan memaparkan dan membahas hasil penelitiannya tentang beberapa jenis penghukuman di Indonesia seperti hukuman mati, kebiri kimia, dan qanun jinayat. Secara umum, Alviani dan Johanna menyinggung bahwa negara beserta instrumen hukumnya harus melindungi warga negara dari perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan berpotensi merendahkan martabat manusia. Selain itu, sebagai amanat dari Pasal 7 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, harus dipastikan bahwa tidak ada manusia yang menjadi objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara ketat.
Terkait dengan hukuman mati, data Kementerian Hukum dan HAM RI pada 2021 menyebutkan bahwa hingga akhir 2021, terdapat 401 warga binaan terpidana hukuman mati, di mana 171 di antaranya menunggu eksekusi di atas lima tahun. Temuan lain dari perkumpulan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyebutkan bahwa terdapat 326 orang dalam daftar tunggu dan 34 orang yang telah dieksekusi hingga 2021. Kasus hukuman mati paling tinggi masih dikenakan dalam perkara narkotika. Angka-angka tersebut merupakan dampak dari aturan hukuman mati yang tersebar di beberapa aturan perundangan seperti KUHP, aturan tindak pidana korupsi, dan aturan tindak narkotika.
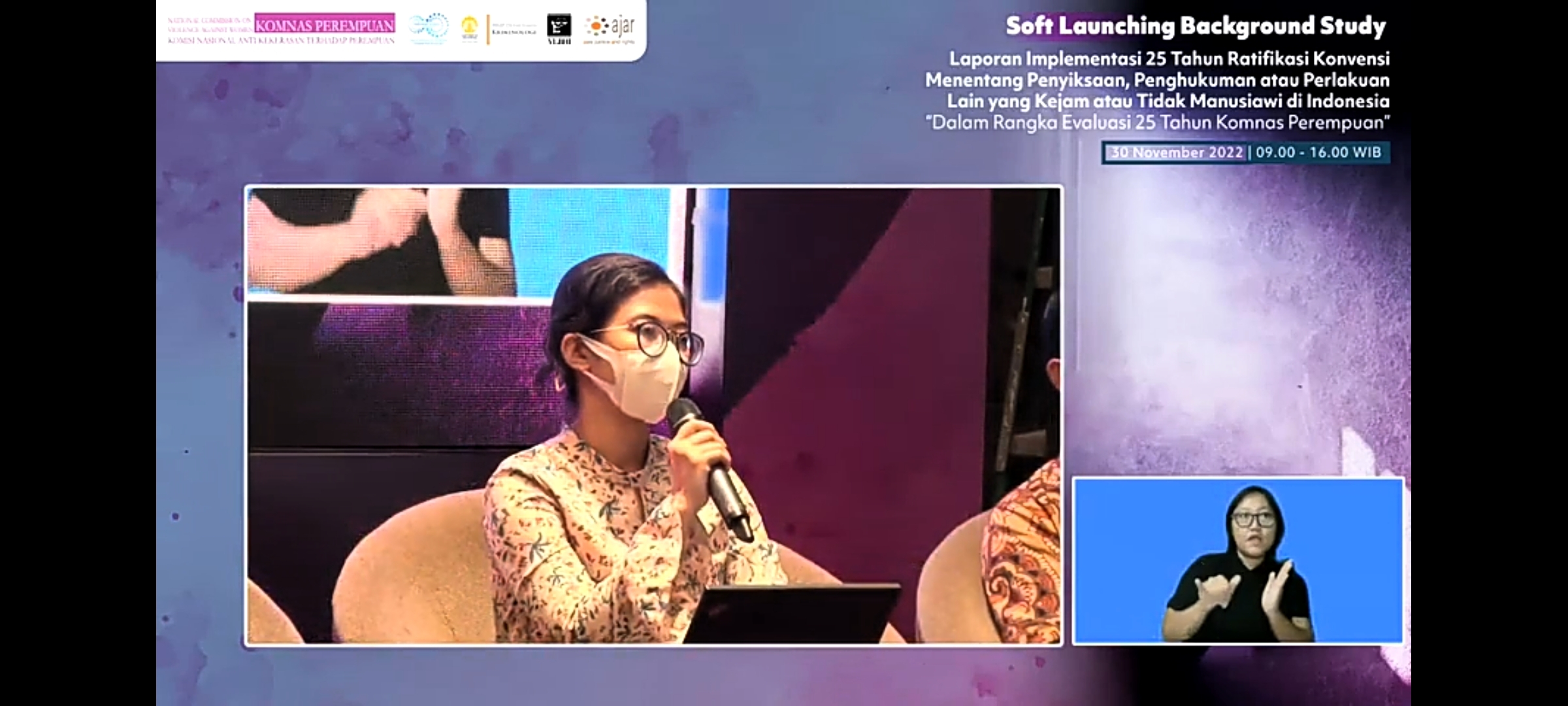
Terkait dengan hal tersebut, Alviani dan Johanna menegaskan bahwa penghukuman mati sebagai upaya pemidanaan tidak sejalan dengan asas restorative justice. Hukuman mati, yang apabila ditarik mundur, dipengaruhi oleh rasionalisasi pemidanaan berbasis pembalasan dendam agar korban mendapatkan keadilan dan menimbulkan efek jera, tidak selaras dengan semangat restorative justice yang mendorong upaya pemulihan korban dan mengembalikan pelaku pada masyarakat agar dapat memperbaiki apa yang sebelumnya telah dirusak, selepas hukuman pidana yang telah dijalaninya. Penghukuman mati juga dianggap tidak tepat dalam upaya pencarian keadilan pada saat menguji proses peradilan yang tengah berjalan. Dalam proses pengujian kasus yang berjalan sangat dinamis, pengadil perlu meminta keterangan secara detail pada terdakwa, yang dalam beberapa kasus akan memakan waktu yang lama untuk mendapatkan putusan dan pertimbangan yang adil. Penghukuman mati dapat segera menutup pintu proses tersebut karena terdakwa sudah ditimpakan eksekusi.

